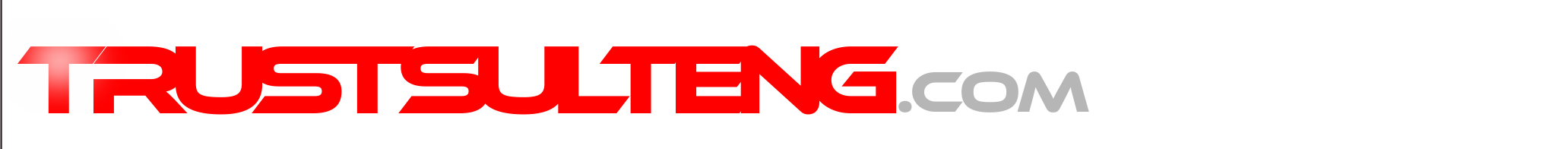Terik matahari Makkah siang itu tidak menyurutkan langkah jutaan manusia yang bergerak perlahan mengelilingi bangunan paling sakral bagi umat Islam, Ka’bah. Di antara lautan kain ihram putih yang seragam, ada satu pemandangan yang berbeda—seorang pria paruh baya berdiri tegak di belakang seorang perempuan renta yang menggenggam tongkat.
Tangannya tidak pernah jauh dari pundak sang ibu, seolah memastikan dunia tetap aman bagi perempuan yang telah melahirkannya.
Dialah Moh. Ridha Saleh, yang akrab disapa Edank. Bagi sebagian orang, Edank dikenal sebagai aktivis, mantan Wakil Ketua Komnas HAM RI, Tenaga Ahli (TA) Gubernur di masa itu, hingga kini anggota satuan tugas (satgas) di Kementerian ESDM. Ia terbiasa berdiri di garis depan memperjuangkan hak orang lain, menghadapi konflik, dan berbicara lantang untuk keadilan.
Namun di hadapan perempuan kecil di depannya, semua identitas itu runtuh.
Ia kembali menjadi seorang anak.
Seorang anak yang pernah digendong, dipeluk, dan dijaga tanpa syarat.
Perempuan itu kini berjalan tertatih, tubuhnya mengecil dimakan usia. Tangannya bergetar, tetapi matanya menyimpan keteguhan yang sama—keteguhan yang dulu membesarkan seorang anak lelaki dari Palu hingga berdiri di panggung nasional.
Siang itu, di pelataran Ka’bah, Edank tidak sedang memimpin rapat, tidak sedang berorasi, dan tidak sedang memperjuangkan kebijakan.
Ia sedang menunaikan janji paling sunyi dalam hidupnya. Janji seorang anak kepada ibunya. Perjalanan ini bukan sekadar ibadah.
Ia adalah perjalanan pulang. Pulang ke akar.
Pulang ke cinta pertama seorang manusia.
Orang-orang di sekeliling mereka mungkin hanya melihat seorang pria membantu ibunya berjalan. Namun di balik langkah-langkah pendek itu, tersimpan puluhan tahun sejarah yang tidak pernah tercatat di dokumen negara.
Ada masa ketika ibunya harus menahan lapar agar anaknya bisa makan. Ada masa ketika ibunya menahan air mata agar anaknya bisa sekolah. Ada masa ketika ibunya berdoa diam-diam agar anaknya selamat menghadapi kerasnya dunia.
Dan kini, di usia senja, doa itu menemukan jalannya sendiri. Ia berdiri di hadapan Ka’bah. Didampingi anak yang dulu ia jaga.
Beberapa saksi yang melihat momen itu mengatakan, “Edank tidak pernah melepaskan ibunya. Tangannya selalu siap menopang. Bahkan ketika ibunya berhenti, ia ikut berhenti. Ketika ibunya lelah, ia menunggu tanpa gelisah”
Tidak ada protokol. Tidak ada jabatan. Tidak ada jarak. Yang ada hanya cinta.
Di wajahnya, tidak terlihat sosok pejabat atau aktivis. Yang terlihat hanya seorang anak yang takut kehilangan ibunya.
Perjalanan mereka belum selesai. Setelah Makkah, mereka melanjutkan ke Madinah—kota Nabi, kota yang bagi banyak orang adalah tempat menemukan ketenangan terdalam.
Di sana, di antara doa-doa yang dipanjatkan, mungkin ada satu doa yang tidak pernah diucapkan keras-keras oleh ka Edank:
“Semoga waktu berjalan lebih lambat.
Semoga ia masih punya kesempatan lebih lama untuk menjaga perempuan yang dulu menjaganya”.
Dalam dunia yang sering diukur dengan jabatan, kekuasaan, dan pencapaian, perjalanan ini mengingatkan satu hal sederhana: Pada akhirnya, setiap manusia hanya ingin kembali menjadi anak di hadapan ibunya.
Dan di pelataran Ka’bah itu, di bawah langit Makkah yang luas, seorang anak dari Palu sedang menunaikan tugas paling mulia dalam hidupnya. Bukan sebagai pejabat. Bukan sebagai aktivis. Tetapi sebagai seorang anak yang mencintai ibunya. (*)